Akhir pekan coba browsing di facebook sesuatu yang menarik dan akhirnya menemukan salah satu notes facebook dengan judul yang menarik, Komikus, Komik dan Kritik Terhadapnya. Ditulis oleh Mas Kurnia Harta Winata yang saya ketahui dari Mas Hiza. Saat ini memang belum pernah ketemu, tapi suatu saat bakal ketemu :D. Saya juga kurang tahu kenapa pakai notes facebook, padahal sekarang sudah tidak terlalu dipakai. Berikut notes facebooknya
—————————–
Hari ini hari yang langka. Saya bertemu dua editor saya dari dua penerbit yang berbeda, di waktu dan tempat yang sama.
Dua-duanya menampar saya. Menyebalkan. Tidak secara fisik memang, tapi tetap saja membekas sampai saya pulang. Yang satu sepertinya tidak disengaja. Yang satu lagi tampaknya sengaja. Mana yang sengaja dan mana yang tidak, tidak perlu saya katakan di sini.
Yang pertama adalah pernyataan bahwa kritik komik di Indonesia mati. Permasalahannya bukan karena tidak ada yang bersedia mengkritik atau tidak ada komik yang layak dikritik. Tapi karena masyarakat komik kita memang nggak tahan kritik. Lucu kan. Biasanya kita menganggap kritikus itu sebagai pihak yang menyerang komikus, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kritikus lah yang diserang komikus beserta penggemar-penggemarnya. Kalau cara-cara kaskus, mungkin kritikus ini ditimpukin bata ramai-ramai sampai nyembah-nyembah minta maaf. Dan saya yakin, komikus yang berkepentingan malah cenderung girang gembira jika mengalami fenomena ini.
Yang kedua adalah pertanyaan, “Apakah komikus Indonesia sadar kalau mereka ini butuh penulis cerita?” Kalau tidak mereka ini super duper hebat, karena ilmu ngomik dan ilmu bercerita adalah hal lain. Sebagai catatan, dalam konteks ini komik semacam Anak Kos Dodol Dikomikin bukan kerja sama antar penulis dan komikus. Karena Dewi Rieka sebagai penulis novel Anak Kos Dodol tidak menulisnya sebagai komik. Pertanyaan susulan yang muncul adalah, “Kalau butuh, adakah yang kompeten dalam hal ini? Sudah adakah ilmunya?” Ilmu menulis komik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ilmu yang berkaitan dengan dramaturgi, pengenalan tokoh, membuat twist cerita, hingga kemampuan mengaduk-aduk emosi penonton. Adakah pendidikan komik mengajarkan hal itu?
Pernyataan matinya kritik komik di Indonesia karena penolakan komikus terhadap kritik dapat kita bantah. Cukup tunjukkan saja bukti-bukti di media sosial. Komikus-komikus, amatir maupun profesional, ramai-ramai mengunggah karya dengan tagline, mohon komentarnya, kripik pedasnya, kritik dan masukan dipersilakan. Ah…
Di saat-saat yang sama, beberapa komik yang diunggah tersebut juga mengangkat tema kritik. Dalam komik tersebut dapat lah kita lihat pandangan komikus-komikus yang bersangkutan dalam menanggapi kritik. Jempol, pujian, dan komentar-komentar yang datang dapat memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat komik kita juga memiliki pandangan yang sama. Coba saya ulang polanya di sini.
Satu tokoh menohok-nohok tokoh utama (yang biasanya merupakan citra diri komikus) dengan kritiknya.
Bla bla bla…
Lalu punch line di panel terakhir. Tokoh utama akan ganti menohok tokoh tukang kritik tadi dengan kenyataan bahwa tokoh tadi; tidak berkarya atau kelakuannya lebih hancur dari tokoh utama yang dikritik.
Jadi apakah saya boleh mengatakan,
Komikus kita mau dikritik. Asal…oleh orang yang ia anggap lebih hebat darinya.
Itulah kebiasaan mayoritas orang Indonesia. Mau dikritik. Asal ada asalnya. Harus membangun. Harus ada solusinya. Harus dari orang yang mampu melaksanakan dan mau melakukan lebih baik dari yang ia kritik.
Maka sudah sewajarnya kritikus kita wafat satu persatu.
Menurut hemat saya, kritik terhadap komik cuma butuh satu syarat. Tidak menyerang pribadi. Yang diomongkan karyanya, bukan tampilan atau kebiasaan sehari-hari komikus. Sudah. Itu saja. Karena kalau tidak, namanya sudah bukan lagi kritik komik. Tapi kritik komikus. Seperti yang saya lakukan barusan.
Kita lanjut untuk mengobrolkan tohokan nomor dua. Saat pertanyaan itu dilontarkan, sungguh benar saya ingin membantah. Ketika saya mengomik, saya pakai ilmu kok. Memangnya saya nggak pakai mikir. Saya rencanakan komik saya. Halaman per halaman. Panel per panel. Sungguh!
Tapi untung saya mampu menelan bantahan sebelum ia keluar dari mulut. Saya sempat menanyakan pada diri saya, “Apakah saya mampu merumuskannya? Karena kalau tidak dapat dirumuskan ia tidak dapat diturunkan. Kalau tidak dapat diturunkan, bagaimana bisa disebut ilmu? Kalau saya bisa, mana buktinya?”
Lagipula, apakah memang ada komik Indonesia yang sempat membuat pencapaian seperti yang mampu dicapai para pendongeng dunia. J. K. Rowling, Akira Kurosawa, L Montgomery, Urosawa Naoki, Adachi Mitsuru, Tim Burton, James Cameron, Pramoedya Ananta Toer.
Saya sadar sepenuhnya saya bisa dibenci banyak orang karena menulis ini. Saya sadar sepenuhnya ke-komikus-an saya yang cuma seupil bisa dicungkil-cungkil.
Tapi saya juga harus jujur. Tidak ada komik Indonesia yang benar-benar baik dalam pencapaian cerita. Baik dari komikus generasi baru atau komikus yang telah dianggap legenda. Saya sudah cukup banyak membaca buku dan menonton film sehingga berani mengatakan pada diri saya sendiri, dan sekarang pada pembaca sekalian. Belum ada komik Indonesia yang mampu menyeret saya ke dunianya, mengaduk-aduk emosi, membangkitkan ketegangan, memberikan perasaan mengambang, dan memaksa saya terjun ke perenungan mendalam mengenai kehidupan.
Selama ini saya memberi standar terlalu rendah pada komik lokal. Komik yang baik adalah mampu bercerita dengan runtut dan membangkitkan emosi dalam diri saya. Komikus yang masuk dalam kriteria ini pun sebenarnya tidak bisa dibilang banyak. Letupan-letupan emosi yang berhasil mereka bangun pun belum dapat dijadikan parameter, karena masih bisa dipertanyakan apakah mereka bisa mengulanginya kembali dengan sadar. Apakah keberhasilan ini hanyalah kebetulan, atau hal yang memang sudah dirancang berdasar kemampuan.
Saya komikus (semi)profesional. Bukan perkara saya mampu mencapainya atau tidak, tapi sudah sewajarnya sasaran pencapaian saya adalah pencapaian para pendongeng dunia. Saya tahu saya punya ilmu. Tapi apakah ilmu saya itu cukup?
Tidak.
Kalau cuma panel, balon kata, tangga dramatik, penokohan, lay out, atau unsur-unsur komik lain yang ada di buku sih saya kenal. Tapi menciptakan karya yang mumpuni tidak cukup hanya dengan itu. Ini nyambung ke pertanyaan editor saya selanjutnya,
“Kalau belum ada ilmunya, bagaimana bisa ngomong ‘bersaing dengan cerita-cerita impor’? Bagaimana tukang cerita kita yang hanya berbekal ilham dan mood mampu bersaing dengan cerita-cerita yang digarap dengan kesabaran, perencanaan matang, dan ilmu-ilmu yang telah mapan?”
Tentu kemampuan tersebut tidak dapat diraih dalam waktu singkat. Dalam konteks komik Indonesia, ini membutuhkan lebih dari satu generasi. Regenerasi kata kuncinya. Semangat yang saya tahu sudah diusung dan dilaksanakan oleh komikus muda semacam Kharisma Jati dan Matto. Namun tanpa rumusan ilmu yang dapat disampaikan secara terstruktur, seberapa efektif regenerasi ini dapat dilakukan? Kalaupun mereka menggunakan sistem “nyantrik”, menggandeng calon komikus untuk bekerja bersama mereka, seberapa banyak waktu dan seberapa banyak komikus yang dapat mereka jangkau?
Kita membutuhkan ilmu yang terstruktur. Yang dihimpun dari segenap pengalaman dan penemuan para komikus lintas generasi yang sudah ada. Sehingga segala jatuh bangun, keringat, dan percobaan dari komikus yang sudah ada tidak sia-sia. Dapat diteruskan ke komikus yang lebih muda, atau bahkan komikus yang lebih berpengalaman sekalipun.
Di sinilah bagian yang hilang dari dunia komik kita. Kritikus komik.
Pihak yang membedah komik. Yang menganalisanya sampai serpihan-serpihan terkecil. Yang mencoba memahami apa yang ingin dicapai komikus. Apa yang seharusnya (dapat) diraih komikus. Apa saja yang telah dilakukan dan dicoba oleh komikus. Apakah komikus tersebut berhasil. Ataukah gagal. Mengapa itu berhasil. Kenapa itu gagal.
Kritikus ini mesti merumuskan analisanya terhadap suatu komik lalu mendokumentasikannya. Sehingga selain menjadi bahan refleksi bagi komikus yang bersangkutan, rumusan itu juga menjadi bahan pelajaran bagi komikus lain! Selama bergenerasi-generasi!
Rumusan-rumusan yang dirangkum inilah yang kemudian bisa kita sebut ilmu. Unsur-unsur yang dapat dipraktekkan dan digunakan sebagai alat analisa. Juga tentunya bisa diturunkan.
Komikus yang tidak tahan kritik dan kritikus yang tidak tahan hujat adalah lingkaran setan. Saya yakin di Indonesia masih ada komikus yang bersedia menerima kritik. (Kalau pun dianggap tidak ada, dengan takut-takut saya menyodorkan diri). Tapi ini tidak serta merta membuat lingkaran setan itu putus. Kalaupun ada kritik pedas yang dilemparkan ke seorang komikus dan tidak membuat komikus itu tersinggung, tetap saja akan ada orang-orang lain yang memandang miring kepada si kritikus tersebut.
Ini selayaknya ditanggulangi dengan bagaimana kritik yang dilontarkan tersebut dapat dirasakan berguna. Bukan cuma oleh yang dikritik, tapi juga oleh masyarakat komik secara luas. Ini bukan saja tanggung jawab kritikus. Ini juga tanggung jawab komikus. Caranya?
Komikus membantu kritikus untuk mengkritik karya-karya mereka.
Komikus membagikan ilmu(mentah)nya, sedangkal apa pun. Yang di sini berarti penemuan pribadinya dalam berkarya, yang ia gunakan sebagai dasar membuat komik. Ilmu (mentah) ini kemudian dapat digunakan sebagai (tambahan) alat analisa oleh kritikus. Baik digunakan sebagai alat analisa untuk komik komikus yang bersangkutan, atau komik komikus yang lain. Dari gabungan pengetahuan berbagai komikus dan analisa berbagai kritikus inilah kita mendapatkan rumusan ilmu. Rumusan ini dapat dirangkum dan diruntutkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan ajar (yang merupakan tugas akademisi).
Budaya menerima dan memahami kritik ini akan berkembang juga menjadi budaya “dewasa” dalam menghadapi editorial komik. Salah satu masalah yang masih dihadapi industri komik Indonesia.
Sedang budaya menganalisa komik menjadi pijakan bagi munculnya editor-editor komik. Di mana editor-editor komik ini tidak lagi harus berasal dari pembuat komik. Yang bagi saya, kurangnya editor komik juga menjadi masalah di industri kita. Dari sekian judul komik Indonesia yang terbit, berapa persen kah yang benar-benar mengalami sentuhan editor yang kompeten? Belum lagi kalau kita menghitung komikus-komikus muda potensial yang tidak merasakan pemertajaman karya oleh editorial sehingga gagal berkembang maksimal?
Nah, karena dalam industri ini saya ada di pihak komikus, maka saya ingin mengajak sesama saya untuk memulainya. Berbagilah pengetahuan dan pengalaman, tahapan, pertimbangan, atau apapun mengenai cara berpikir kalian saat membangun komik. Ajakan ini juga tertuju kepada saya, yang sering malas dan enggan membuang energi. Setahu saya, baru Sweta Kartika yang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya percaya masih ada yang lain. Tapi mohon dimaklumi, selain kurang gaul saya ini juga pikun.
Dan saya berdoa agar para kritikus komik diberkahi keberanian dan ketahanan mental. Terpujilah orang-orang seperti Muhammad Hadid dengan Akademi Sekuensialnya yang masih berani mempublikasikan kritik komik.
Pernah ia mengaku pada saya, gentar mengkritik komik karena ia sendiri tidak membuat komik. Sedang saya, gentar mengkritik komik karena saya sendiri juga membuat komik.
Klop dah! Semoga dunia perkomikkan Indonesia semakin mengasyikkan 🙂
2 Mei 2013, Sanggar KOEBUS, Yogyakarta


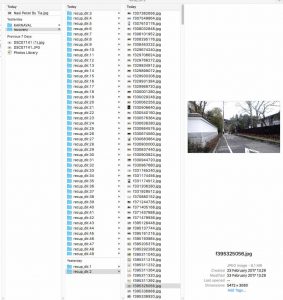


Leave a Comment